
AI, Ketimpangan Digital dan Disparitas Tak Kasat Algoritma
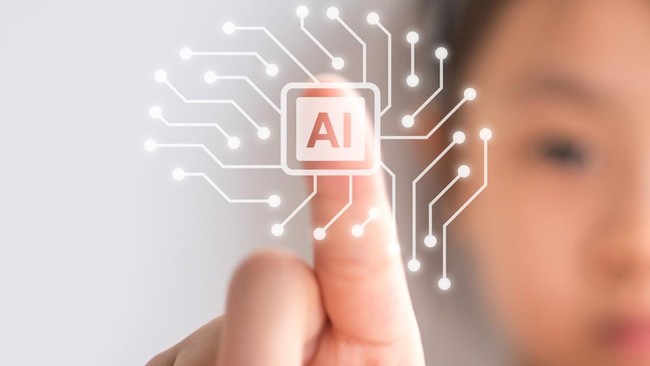
Indonesia tengah mewujudkan impian besar yakni membangun kekuatan ekonomi digital pada 2045. Bukan perkara mudah lantaran masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Teknologi dengan cepat bergerak. Salah satunya soal artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan kini tengah jadi primadona.
Pertanyaannya adalah, sudah siapkah kita?
Saya berbincang dengan Perwakilan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) untuk Indonesia, Filipina, dan Timor Leste Marco Kamiya Juli lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam perbincangan itu, Kamiya mengatakan tantangan tersebut salah satunya adalah soal keamanan siber.
Menurutnya di saat sebagian elite berbondong-bondong menggaungkan"lompatan teknologi", ada pelaku usaha yang memutus sambungan internet. Bukan karena tak ingin maju, tapi karena takut menjadi korban serangan ransomware.
Belum lagi dari hasil survei Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia yang mencatat 70 persen UMKM masih kesulitan akses pembiayaan untuk go digital.
Inilah paradoks yang kita hadapi. Mimpi besar tentang masa depan digital tak diiringi jaring pengaman yang memadai.
Lihat Juga : |
Dalam ingar-bingar adopsi AI, sering kali kita larut dalam euforia teknologi dan lupa bertanya: kesenjangan macam apa yang sedang terjadi?
Di Indonesia, ketimpangan ini bukan cuma soal akses, tapi juga soal kesiapan SDM, lemahnya perlindungan data, dan kebijakan yang belum padu.
UMKM masih tertatih, sementara publik makin resah soal keamanan datanya. Ini bukan sekadar tantangan teknis, lebih kepada ketimpangan sistemik yang hanya bisa dijawab dengan keadilan, bukan sekadar kecanggihan algoritma.
"AI bisa menjadi alat lompatan teknologi, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia," kata Kamiya.
"Teknologinya sudah ada, tapi negara dan perusahaan belum tahu bagaimana cara menyerap dan mengaplikasikannya," imbuhnya.
Kata kuncinya adalah disparitas atau ketimpangan. Timpang pada akses teknologi yang berujung pada ketimpangan pemahaman, perlindungan, dan peluang. Ketika literasi digital belum merata dan sistem perlindungan masih rapuh, AI hanya akan memperluas jurang ketimpangan dan menjauhkan akses dari mereka yang paling rentan.
Dan kita bicara soal risiko nyata. Bukan cuma kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan kontrol atas data.
Dalam sistem berbasis AI, algoritma mampu menembus lapisan keamanan yang lemah dan menyusup ke sektor-sektor vital seperti perbankan dan kesehatan. Jika tak dibarengi dengan kebijakan keamanan siber yang kuat dan mudah dipahami masyarakat, maka ketakutan publik bukan paranoia, tapi bentuk kewaspadaan rasional. Survei Ipsos Flair Indonesia 2023 mencatat 92 persen masyarakat Indonesia khawatir datanya disalahgunakan, dan menjadi angka tertinggi di Asia Tenggara.
Global Innovation Index 2024 melaporkan hanya 0,28 persen dari produk domestik bruto kita yang digunakan untuk riset dan inovasi. Bandingkan dengan negara-negara maju yang rata-rata sudah di atas 2 persen. Bahkan Korea Selatan cukup ambisius dengan menginvestasikan 4 persen. Ini artinya, kita ingin jadi pemain besar di arena AI global, tapi datang ke gelanggang tanpa persiapan strategi, bahkan mungkin tanpa perisai dan amunisi.
"Banyak kemajuan tidak lahir dari penemuan baru, tapi dari upaya melakukan hal lama dengan cara yang lebih baik," ujar Professor Sir Mike Gregory dari University of Cambridge. Ia mengingatkan bahwa kita sering terjebak glorifikasi inovasi, padahal akar masalah ada pada kegagalan implementasi dan sinergi kebijakan.
Lebih dari sekadar menyoal AI, ini refleksi arah pembangunan kita. Tentang siapa yang mendapat tempat di masa depan, dan siapa yang terpinggirkan karena sistem tak "mampu" membaca keberadaannya(?)
AI memang menjanjikan efisiensi. Tapi jangan sampai ia justru memperdalam eksklusi. Kita butuh kebijakan yang bukan hanya pro-teknologi, tapi pro-kesetaraan, pro-kepercayaan, dan yang terpenting, human-centered atau berpihak kepada kemaslahatan manusia.
Saya percaya kemajuan masa depan tak bisa dihindari, akan tetapi kita juga tak boleh didikte sepihak oleh mereka yang paling kencang bersuara atau paling cepat berlari. Sebab masa depan bukan milik mereka yang duluan datang, tapi milik semua yang diajak bersama.
Pertanyaannya, apakah kita sedang membangun masa depan (bersama), atau sekadar memindahkan ketimpangan lama ke dalam bentuk digital yang lebih rapi dan kasat algoritma?
Kebijakan membumi
Tantangan terbesar kita bukan pada lambatnya adopsi teknologi, tapi pada kebijakan yang tercerai-berai. Strategi Nasional (STRANAS) AI yang diluncurkan pada 2020 masih bersifat non-binding atau tidak mengikat.
Ketika di atas kertas impian masa depan terlalu digantungkan pada rencana besar, terkadang kerap lupa menyiapkan jalannya. Apalagi di saat sebagian pemerintah daerah masih meraba urgensi digitalisasi, sektor swasta melaju dengan ritme sendiri, sementara kampus-kampus sibuk menghasilkan jurnal yang belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan praktis pelaku industri.
Di sinilah letak masalahnya di mana support yang ada masih bersifat parsial, bahkan terkesan hanya untuk segelintir. Belum inklusif, belum menyentuh akar.
Saya pernah mewawancarai seorang pemimpin C-suite dari salah satu bank terkemuka di Indonesia, yang menekankan bahwa risiko dalam sektor keuangan bisa sangat besar jika pemanfaatan AI tidak disertai kehati-hatian, terutama dalam menjaga keamanan data yang sangat sensitif. Ia menyebut keamanan sebagai kunci utama, bukan pelengkap.
Hal ini mempertegas bahwa dalam ekosistem digital, kesenjangan tidak hanya terjadi pada akses teknologi, tapi juga pada kesiapan menghadapi risikonya. Ketika sektor-sektor besar bisa mengantisipasi dengan sistem perlindungan berlapis, bagaimana dengan UMKM, komunitas lokal, atau lembaga pendidikan yang tak punya perlindungan serupa?
Jika tak segera dijembatani, kesenjangan ini bisa membuat transformasi digital justru melanggengkan ketidaksetaraan lebih dalam, yang kasat, sekaligus terlewat oleh algoritma.
Solusinya bukan menunggu kebijakan besar berikutnya, tapi membangun dari bawah. Kita perlu ekosistem digital yang membumi dengan melibatkan UMKM, komunitas adat, pekerja informal, anak muda di daerah tanpa sinyal stabil.
Kita juga butuh pendampingan digital yang nyata, bukan pelatihan instan. Pemerintah perlu memberi insentif bagi yang berani mencoba, gagal, dan terus belajar dalam proses transisi ini.
Universitas dan media punya peran krusial sebagai penghubung antara industri, pemerintah, dan masyarakat sipil. Seperti inisiatif Babbage Forum di Cambridge yang dipimpin Prof. Mike: "Kita perlu ruang dialog yang terbuka, aman, dan setara. Sebab yang kita kejar bukan hanya transformasi digital, tapi keadilan tentang siapa yang bisa mengakses dan merasakan manfaatnya."
Inklusivitas bukan pelengkap. Ia adalah syarat mutlak bagi masa depan yang adil dan lebih cerah.
(sur/sur)[Gambas:Video CNN]



